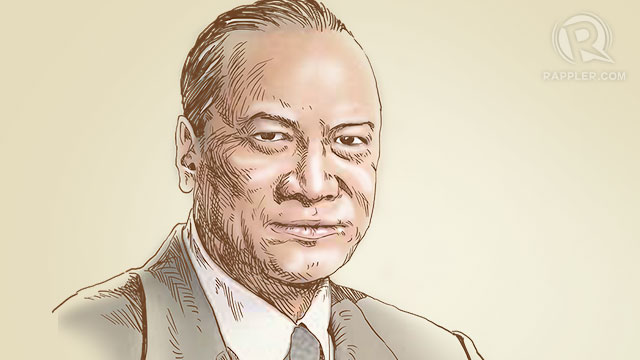Dokter dalam bencana
keren989
- 0
MANILA, Filipina – Pada bulan Juli 1990, gempa bumi melanda Luzon Tengah dan Utara, menewaskan ratusan orang dan menghancurkan ribuan rumah. Dari tim penanggulangan bencana yang dikirim untuk membantu para penyintas, ada satu yang menonjol: Satuan Tugas Kesehatan Mental.
Dr Lourdes Ignacio ingat sambutan yang mereka terima ketika orang pertama kali mengetahui siapa mereka dan apa yang mereka lakukan: mereka ditolak.
“Tidak ada pasien gangguan jiwa di sini. Kami tidak membutuhkanmu,” dia ingat kata-kata mereka.
Warga enggan berbicara dengan mereka karena takut dicap gila. Kami membutuhkan makanan dan pakaian, kata mereka, bukan psikiater.
Namun seiring negara ini melewati bencana demi bencana, para dokter kini berusaha menekankan pentingnya menangani kesejahteraan psikologis dan emosional para penyintas.
Bulan Desember 2012 lalu, Topan Pablo melanda Mindanao, menewaskan lebih dari seribu orang dan berdampak pada jutaan orang. Masyarakat di daerah yang terkena dampak paling parah seperti Lembah Compostela dan Davao Oriental menghabiskan Hari Natal di rumah-rumah yang hancur dan menyambut Tahun Baru dengan ketidakpastian.
Para penyintas dalam situasi ini tidak hanya membutuhkan bantuan materi. Setelah seharian mencari makan dan berjuang untuk membangun kembali kehidupan mereka, terkadang yang mereka perlukan hanyalah mengungkapkan apa yang mereka rasakan, dan menemukan orang yang bersedia membantu.
Ketakutan dan kesedihan
Sambutan awal yang tidak diinginkan kepada profesional kesehatan mental mencerminkan stigma yang terkait dengan profesi tersebut. Bagi kebanyakan orang, kata “spiritual” identik dengan orang gila dan kekerasan.
Namun Ignacio mengatakan psikiater tidak hanya peduli pada diagnosis klinis gangguan mental.
Dalam sebuah artikel di World Psychiatry Journal, Prof Mario Maj dari Universitas Naples mengatakan psikiater kini dipanggil untuk menangani “masalah kesehatan mental”, dengan mengutip contoh tekanan psikologis serius pada orang-orang yang menderita setelah bencana alam.
Ignacio menjelaskan, menderita rasa takut, sedih, dan putus asa tidak serta merta disamakan dengan gangguan jiwa. Ini, katanya, adalah reaksi normal terhadap kejadian tidak normal. Diagnosis ditegakkan bila gejala-gejala tersebut mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari seseorang dalam jangka waktu yang lama.
Seni mendengarkan
Selama 23 tahun bekerja dalam upaya tanggap bencana, perawat Thelma Barrera telah menyaksikan perlahan namun semakin meningkatnya penerimaan terhadap pekerjaan mereka di antara orang-orang yang mereka layani.
Barrera adalah direktur program program Layanan Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial (MHPSS) di Pusat Kesehatan Mental Nasional. Dia dan timnya telah memberikan layanan psikososial kepada para penyintas bencana alam dan akibat ulah manusia selama dua dekade terakhir. Responsnya pun sama: mereka menginginkan makanan, bukan orang untuk diajak bicara.
Dia tahu bahwa keadaan akhirnya mencapai titik balik pada tahun 2011 ketika kebakaran terjadi di Navotas yang berdampak pada setidaknya seratus rumah tangga.
Barrera menceritakan bagaimana seorang wanita berlari ke arah mereka saat tim berjalan menuju area tersebut.
Dia bertanya: ‘Psikososial Anda? Psikososial? hei terima kasih, psikososial!’” kata Barrera. “Dia sangat senang melihat kami. Wanita itu baru saja mulai berbicara kepada kami tanpa henti.”
Selama hampir 10 menit, wanita tersebut menceritakan pengalamannya setelah kebakaran, sementara Barrera hanya berdiri di sana dan mendengarkan. “Saya merasa lebih baik, terima kasih, ”Barrera mengingat perkataannya. “Banyak yang memberi makanan, tapi tidak ada yang mendengarkan.“
Mulai dari korban hingga penyintas
Dampak suatu bencana terhadap masyarakat bergantung pada beberapa faktor, seperti durasi dan sifat bencana, pengalaman spesifik yang dialami oleh korban, dan ketersediaan dukungan sosial dalam waktu dekat.
Apa yang dilakukan Ignacio, Barrera dan tim psikososialnya di daerah bencana disebut layanan psikososial. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada sesi pembekalan, namun mereka menekankan bahwa dukungan psikososial lebih dari sekedar berbicara dengan para penyintas dan memungkinkan mereka untuk menceritakan kisah mereka.
Dukungan psikososial menjawab kebutuhan emosional, sosial, spiritual dan spiritual seseorang untuk kesejahteraan psikologis dan emosionalnya. Untuk melakukan hal ini, baik para penyintas, masyarakat yang terkena dampak, maupun unit pemerintah daerah harus terlibat.
Ignacio berpendapat bahwa ini adalah cara yang lebih memberdayakan untuk memandang para penyintas: dengan lebih berfokus pada ketahanan dan kemampuan mereka untuk pulih, dibandingkan berfokus pada trauma dan stres yang mereka rasakan.
“Bencana adalah pengalaman komunitas orang yang saling mempengaruhi,” katanya. “Agar seseorang dapat pulih dari bencana, ia memerlukan sistem dukungan sosial – komunitas, tata kelola yang baik, dan bantuan ekonomi. Namun sebuah komunitas juga harus memiliki individu-individu yang berfungsi secara sehat dan akan aktif berupaya untuk melakukan pemulihan.”
Korban yang tersembunyi
Memiliki fasilitator yang terlatih adalah penting dalam sesi pemrosesan. Barrera mengatakan tidak mudah melakukan pekerjaan seperti yang mereka lakukan, meskipun tampaknya hanya sekedar mendengarkan.
“Empati adalah sebuah keterampilan,” jelasnya. “Anda menempatkan diri Anda pada posisi orang lain, tanpa lupa bahwa Anda tidak berada pada posisi itu.”
Tidak semua orang cocok untuk pekerjaan seperti itu, tidak juga ketika orang-orang dalam keadaan linglung, tidak berdaya dan menangis. Sebagai pekerja sosial, Barrera mengatakan mereka tidak seharusnya menangis bersama mereka. “Karena ini tentang Anda,” kata Barrera. “Ini harus selalu tentang mereka yang selamat.”
Namun bahkan dengan pelatihan dan berjam-jam di lapangan, beratnya tindakan yang mereka lakukan masih dapat menghambat respons terhadap bencana. Barrera mengingat satu sesi yang dia lakukan dengan anak-anak setelah pembantaian Maguindanao. Pada tahun 2009, 58 orang terbunuh – sebagian besar adalah jurnalis – dalam kekerasan terkait pemilu terburuk dalam sejarah Filipina.
Barrera meminta anak-anak menggambar dan menulis sebagai cara mengungkapkan perasaan mereka. Ketika dia meminta mereka untuk membagikan karyanya kepada kelompok tersebut, seorang gadis berusia 14 tahun dengan sukarela membagikan puisinya—tetapi alih-alih membacanya, dia malah bernyanyi.
“Dia bernyanyi dengan sangat baik, dan dia menangis saat menyanyikannya,” kenang Barrera. “Lagu itu dalam bahasa Maranao. Ketika saya memintanya menjelaskan dalam bahasa Tagalog tentang apa itu, dia menjawab itu untuk ibunya. Itu adalah caranya memberi tahu ibunya betapa dia mencintai dan merindukannya.”
Barrera mengatakan bukan hanya para penyintas yang membutuhkan pemrosesan psikososial – bahkan petugas bantuan juga merupakan korban tidak langsung. Mereka disebut sebagai korban tersembunyi: para responden dan orang-orang yang terkena dampak bencana terhadap masyarakat.
“Kami berbicara dengan tentara, pejabat pemerintah setempat, bahkan media,” kata Barerra. “Kadang-kadang mereka tidak bisa mengatasi stres melihat begitu banyak orang terkena dampaknya, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa.”

Strategi dukungan
Penerimaan komponen psikososial dalam tanggap bencana telah meningkat pesat sejak tahun 1990, namun Barrera dan Ignacio berpendapat masih ada ruang untuk perbaikan dalam penerapan dan pemahaman konsep tersebut.
Layanan ini tidak hanya memerlukan fasilitator terlatih dan dukungan pemerintah. Strategi untuk membantu para penyintas mengatasi bencana dan membangun kembali kehidupan mereka juga harus relevan dengan kebutuhan mereka. Ignacio yakin inilah kekurangan dari sebagian besar operasi bencana.
“Pikirkan kehidupan manusia. Apa yang dirasakan para penyintas? Mereka tidak hanya membutuhkan makanan, pakaian, rumah,” katanya. “Humanisasi itu perlu.” (Ada kebutuhan akan kemanusiaan.) – Rappler.com