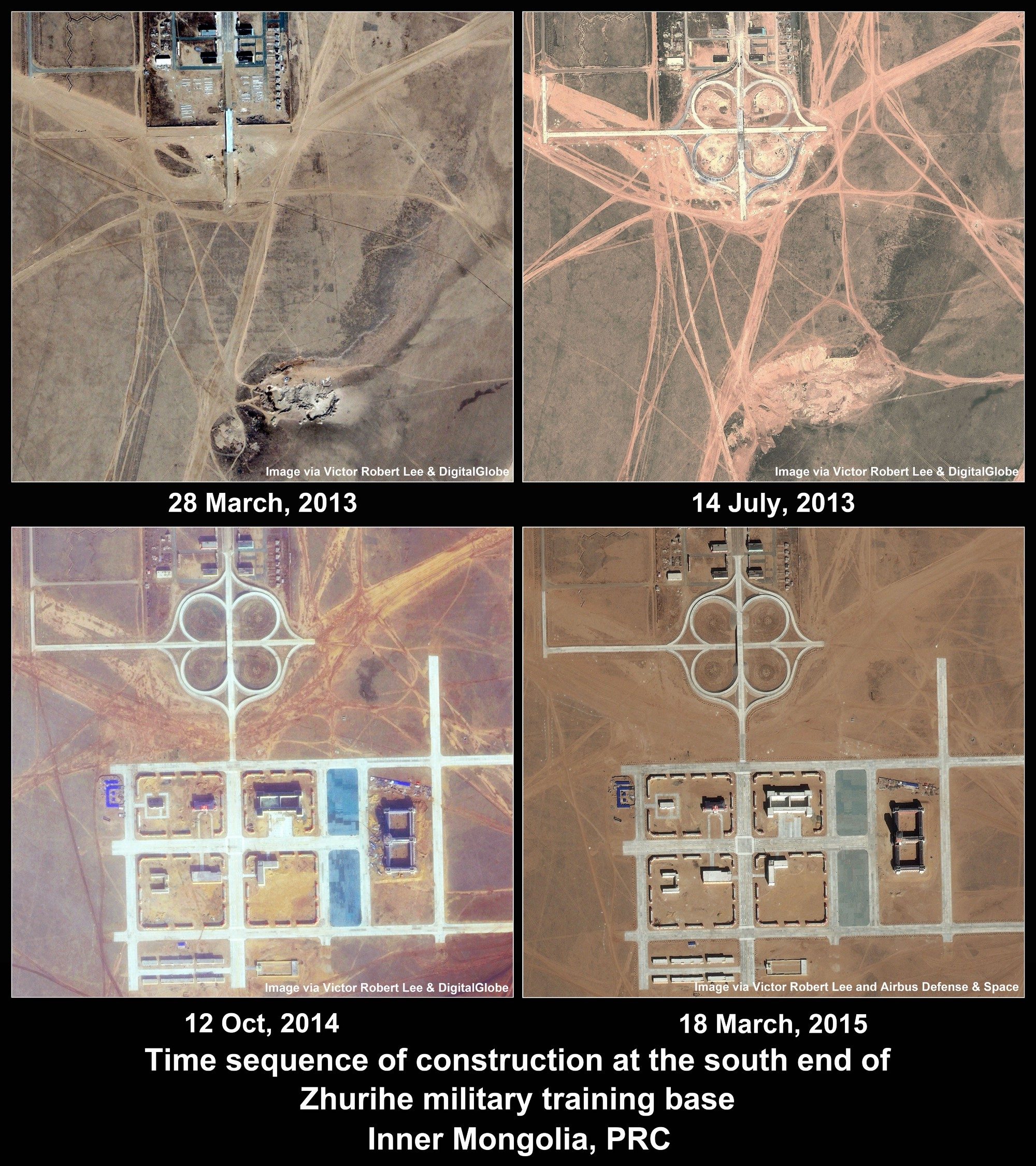Apa yang membuat seseorang menjadi orang Indonesia?
keren989
- 0
Mengapa Indonesia? Ini adalah pertanyaan yang terus menerus dilontarkan kepada saya sejak saya pindah ke negara ini.
Dalam kebanyakan kasus, saya memberikan jawaban yang paling mudah agar orang-orang dapat melepaskan diri dari pertanyaan saya: Karena ini adalah negara yang hebat. Karena orang-orangmu seksi. Budaya Anda jauh lebih baik daripada yang kami miliki di rumah.
Ini adalah jawaban-jawaban manis yang saya tahu sebagian besar dari Anda ingin mendengarnya dari seseorang yang berasal dari negara yang tidak terlalu berbeda dengan negara Anda. Kita juga mempunyai jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Politisi yang korup. Infrastruktur yang konyol. Kualitas pendidikan masyarakat yang buruk. Saat diminta menunjukkan foto negaraku, aku sering mendapat jawaban seperti, oh, Indonesia jauh lebih baik. Saya kemudian setuju.
Soalnya, saya tidak punya banyak waktu untuk memperdebatkan hal ini. Saya juga tidak ingin mengabdikan sebagian besar hidup saya untuk menyakiti harga diri teman-teman saya. Suatu ketika seorang teman bertanya berapa nilai peso Filipina jika dikonversikan ke rupiah. Saat ini, satu peso berada di kisaran Rp 300. Dia segera berkata, kalau begitu, nilai uang kami lebih besar daripada uang Anda. Saya hanya tersenyum. Tentu saja sebaliknya.
Salah satu alasan utama aku menutup bibir ketika terpojok untuk menjawab pertanyaan seperti ini adalah karena aku takut aku akan mendapat lebih banyak musuh daripada teman dengan melampiaskan pikiranku dengan lantang.
Pertanyaan tersebut juga akan mengungkapkan seberapa pribadi migrasi saya ke Indonesia.
Bagaimanapun, ini bermula dari kisah pribadi tiga tahun lalu di Filipina bagian selatan, dekat perbatasan laut yang memisahkan kedua negara kita.
Temui Sangir
Ceritanya tentang orang-orang Anda yang bermigrasi ke Filipina pada tahun 1950-an. Mereka menyebut diri mereka orang Sangir, suku kepulauan kecil di Sulawesi Utara.
Jumlahnya ribuan yang tinggal di Pulau Balut dan Sarangani. Terkadang mereka menyebut diri mereka orang Indonesia. Di lain waktu, mereka menganggap diri mereka orang Filipina, terutama generasi baru Sangir yang belum pernah melihat Indonesia.
Hanya beberapa hari sebelum Natal tahun 2012, saya berlayar ke Mabias, pelabuhan di provinsi Sarangani di Filipina yang secara politik merupakan milik kedua pulau tersebut.
Perjalanan ini memakan waktu 8 jam dari General Santos City dengan menaiki kapal feri berukuran sedang yang membawa karung beras, ayam, ayam aduan, kambing, peti soda botolan, dan orang-orang yang pulang dari pulau utama Mindanao di Filipina selatan.
Tepat sebelum kami hendak menaiki kapal, kami diberitahu bahwa kapal tersebut tidak lagi menerima penumpang. Telah mencapai kapasitas penumpang maksimal, sehingga perjalanan selanjutnya akan mengangkut penumpang pada bulan Januari tahun berikutnya. Saya sedang berdebat apakah mungkin untuk ikut serta karena saya terburu-buru mengumpulkan fakta dari sebuah cerita yang akan segera dirilis. Akhirnya, setelah berbicara dengan salah satu penjaga pantai, kami bisa terjun.
Di Pakiluaso, sebuah desa pesisir kecil yang berpenduduk sekitar 30 keluarga di Pulau Balut, saya bertemu Nerlyn Sasamu Dagcutan. Seorang wanita berkulit gelap dan bertulang besar, Dagcutan adalah a guru, istilah bahasa Indonesia untuk wali. Sebagai seorang wali, tugas utamanya adalah melatih para pemuda Sangir untuk berbicara Bahasa Indonesia, bahasa nasional negara Anda.
Berbeda dengan banyak universitas negeri di mana dosen dapat mempresentasikan materinya dengan proyektor multimedia, Dagcutan duduk hanya dengan sepotong kapur dan papan tulis berdebu di dalam sekolah beton seluas 20 meter persegi yang mereka “pinjam” pada hari Sabtu. Sekolah tersebut kebetulan dimiliki oleh pemerintah Filipina, di mana siswanya mendapatkan pendidikan seperti orang Filipina pada hari kerja.
Dagcutan mempunyai tugas mulia lainnya di hari Sabtu. Selain belajar Bahasa Indonesia, ia juga mengajari anak-anaknya menyanyikan lagu-lagu seperti “Dari Sabang Sampai Merauke”.
Dalam bahasa Inggris, seperti yang Anda tahu, lagunya berbunyi: “Dari Sabang sampai Merauke pulau-pulaunya bertumpuk, saling terhubung, menjadi Indonesia.”
Anak-anak menghafalkan lagu tersebut, tanpa tahu di mana letak pulau-pulau tersebut, atau memahami apa arti sebenarnya dari lagu tersebut. Namun, dia mengatakan kepada Dagcutan bahwa penting bagi anak-anak untuk belajar tentang tanah air mereka.

Saya menceritakan kisah mereka kepada Anda karena banyak dari Anda yang tidak diragukan lagi adalah warga negara dan penduduk negara Anda terkadang terlibat perkelahian kecil.
Pada bulan April, salah satu seniman ternama dunia, Anggun Cipta Sasmi, dan salah satu kebanggaan negara, menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowiyang memohon kepadanya untuk memberikan grasi kepada mereka yang akan dieksekusi pada bulan itu.
Tapi membaca komentar online, saya melihat beberapa dari Anda mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya urusan untuk ikut campur dalam masalah Indonesia. Dengan pindah ke Prancis, kata Anda, dia kehilangan dominasi moralnya untuk mengungkap masalah ini. Dia bukan lagi orang Indonesia, katamu.
Pandangan ini membawa saya kembali ke orang-orang seperti Dagcutan dan the lebih dari 6.000 orang keturunan Indonesia tinggal di Mindanao.
Jika ini terjadi pada Anggun yang terkenal itu, saya khawatir rakyat Anda di Filipina akan mengalami nasib yang sama. Bagaimana jika mereka mulai meminta Jokowi untuk melihat penderitaan mereka sebagai orang-orang yang secara de facto tidak memiliki kewarganegaraan, apakah Anda juga akan mempertanyakan identitas mereka karena mereka tidak lagi tinggal di Indonesia?
Tidaklah berlebihan untuk berpikir bahwa orang-orang ini sudah lama ingin menyampaikan penderitaan mereka kepada pemerintah pusat.
Hal serupa juga terjadi di negara saya.
Veronica Pedrosa, seorang jurnalis internasional yang orang tuanya terpaksa tinggal di pengasingan di London pada masa pemerintahan mendiang diktator dan mantan presiden Ferdinand Marcos, pernah mengaku bagaimana kewarganegaraannya akan dipertanyakan “ketika saya berbicara di Filipina.”
Hari ini, saat negara Anda berusia 70 tahunst merdeka dari Belanda, saya bertanya: Apa yang menjadikan orang Indonesia?
Apakah dengan menjadi pemegang KTP dan menjadi warga negara bawaan, mampu berbicara bahasa nasional sudah cukup untuk menjadikan seseorang sebagai orang Indonesia?
Globalisasi telah meruntuhkan tembok-tembok, dengan terbentuknya identitas-identitas baru dan beberapa di antaranya memudar. Orang-orang melintasi batas negara untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Saat ini, generasi baru berharap dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah. Namun, ada beberapa hal yang cukup sensitif saat ini. Bahasa, kata beberapa dosen saya, merupakan salah satu pilar jati diri bangsa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mengadopsi bahasa Inggris mempengaruhi identitas Indonesia seseorang.
Nasib dan masa depan yang sama
Benedict Anderson, seorang sarjana Indonesia kontemporer, setuju bahwa bagian dari proyek nasionalisme adalah bahasa bersama. Namun ia juga mengatakan bahwa “nasionalisme muncul ketika, di wilayah fisik tertentu, penduduknya mulai merasa bahwa mereka mempunyai nasib yang sama, masa depan yang sama.”
Masa depan bersama seperti apa yang bisa kita capai jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya membawa kabar baik bagi masyarakat kelas menengah dan atas, dan tidak bagi 40% masyarakat miskin yang hidup di bawah $2 per hari.
Masa depan bersama apa yang bisa kita capai jika supremasi hukum tidak lagi terlihat?
Bukankah nasionalisme seharusnya lebih dari sekedar bahasa yang kita gunakan?
Menarik untuk menelusuri jati diri bangsa Dagcutan: selain a hubungan, dia juga seorang pemimpin desa di Pakiluaso. Undang-undang Filipina umumnya tidak mengizinkan orang asing mencalonkan diri untuk jabatan publik. Seperti halnya di Indonesia, penerapan undang-undang di Filipina mempunyai cerita yang berbeda, dan hal ini justru menguntungkan Dagcutan.
Faktanya, surat suara di Indonesia menjangkau seluruh pulau; dan suaranya dihitung pada setiap pemilu legislatif dan pemilu presiden. Meski terkadang hal seperti ini hanya menambah krisis identitas mereka: Apakah kita orang Indonesia atau orang Filipina?
Sebagai orang Indonesia, mereka selalu mengunjungi kampung halamannya sebulan sekali, kata Alfrede Lahabir, warga Indonesia lainnya yang tinggal di Pulau Balut, kepada saya tiga tahun lalu.
Lahabir, seorang nelayan, melakukan hal ini untuk bertemu kerabatnya pada acara-acara khusus. Saya ingat dia pernah mengajak saya untuk ikut bersamanya ke Matutuang, bagian dari gugusan pulau Sangihe. Dengan menggunakan perahu, dia menceritakan kepada saya bahwa kami dapat mencapai kawasan itu dari Balut antara 3 dan 6 jam.

Pertanyaan tentang identitas Indonesia adalah sesuatu yang saya ingin Anda jawab. Pada akhirnya, sebagai jurnalis, saya yang melontarkan pertanyaan, bukan sebaliknya.
Kisah-kisah keluarga Sangir membentuk kehidupan saya sebagai pemegang kewarganegaraan Filipina yang “sah”. Banyak dari kita tidak melihat ini sebagai sebuah masalah. Kita tidak tertidur sambil memikirkan siapa diri kita sebenarnya. Akta kelahiran dan paspor saya menunjukkan bahwa saya orang Filipina. Anda orang Indonesia karena KTP Anda menyatakan demikian.
Namun bagi masyarakat seperti Dagcutan dan Lahabir, mereka dianggap asing di negeri tempat mereka tinggal. Sebagai warga negara non-Filipina, mereka seringkali kesulitan dengan kepemilikan tanah dan akses terhadap asuransi yang disponsori pemerintah. Sekali lagi, ini adalah masalah yang tidak harus kita lalui karena pemerintah mengakui kita sebagai warga negaranya
Saya datang ke Indonesia untuk menyampaikan pertanyaan mereka ke sini.

Pada hari saya bersiap meninggalkan Pulau Balut tiga tahun lalu, salah satu anak Lahabir bertanya kepada saya, “Kapan kamu kembali?”
“Saya tidak tahu, setelah (Sangire untuk pecandu),” jawabku. Saya tidak tahu.
Aku duduk di depan perahu agar mereka tidak bisa menangkapku menangis ditelan laut.
Dua tahun kemudian, saya bergabung dengan Rappler sebagai reporter bisnis.
Namun cerita Sangir begitu rumit sehingga suara mereka sering menghantui saya saat saya tidur. kapan kau kembali Anda harus menceritakan lebih banyak kisah kami.
Hari ini saya berada di sini di negara yang mereka bayangkan sebagai rumah mereka. – Rappler.com
Mick Basa sedang menempuh studi pascasarjana Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Dia adalah reporter bisnis Rappler di Manila sebelum pindah ke Indonesia.