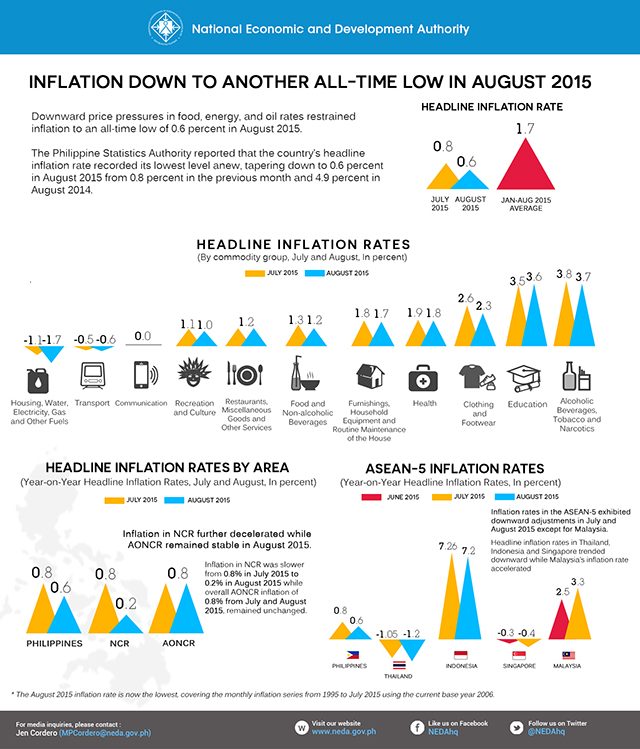Sebelum Anda memutuskan untuk memakai hijab
keren989
- 0
Pada tahun 2002, ketika saya memutuskan untuk berhijab, orang tua saya melarang saya. Ayahku bilang, hijab itu tidak wajib. Kata ibuku, hijab tidak membuat wanita menjadi lebih cantik. Kecantikan wanita tidak akan tereksplorasi dengan memakai jilbab.
Rambutku yang hitam, keriting, dan terkulai, tidak bisa lagi diikat ekor kuda atau sekadar diikat dengan pita. Namun keputusan saya sudah diambil, padahal saat itu usia saya belum genap 20 tahun, saya memutuskan untuk berhijab.
Saya tidak takut, meski kakak saya mengancam dengan mengatakan: “Saya harap kamu tidak membakar hijabmu,” katanya. Adikku masih trauma karena hijabnya pernah dibakar oleh ayahku.
Mengapa saya memutuskan untuk memakai hijab? Alasannya sederhana. Hari itu, 3 Februari 2002, saat berada di pengajian Daurat Tauhid Bandung, saya mendengarkan ceramah gimnastiar Abdullah “Aa Gym”. Hati saya tergerak.
Lupakan ayat-ayat. Alasannya sangat sederhana, karena ia ingin menjadi anak perempuan yang bertakwa kepada orang tuanya. Kedengarannya tidak bersalah ya.
Tapi apakah itu benar? Tentu saja jawabannya tidak semulus itu. Perjalanan berhijab selama 13 tahun menyadarkan saya bahwa masa bulan madu berhijab akan segera berakhir di tahun kedua pemakaian.
Perjalanan berhijab selanjutnya datang bukan dari perdebatan batin, melainkan dari pertarungan pemikiran dan stigma masyarakat.
Saya tetap seperti yang saya minta
Dengan baik. Aku memutuskan untuk memakai hijab. Tapi tunggu, itu 1 persen dari keputusan dalam hidup saya. Saya juga memutuskan dengan siapa saya bergaul, buku apa yang saya pilih, dan profesi apa yang saya tekuni.
Ketika saya berhijab, bukan berarti saya membatasi pergaulan saya. Saya percaya, seseorang akan menemukan pengalaman spiritualnya dari orang-orang disekitarnya.
Dari pada kita seperti ceramah ustaz di kampus saat kuliah di Universitas Airlangga Surabaya, agar terhindar dari orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita sehingga kita istiqomah di jalan-Nya aku adalah kebalikannya.
Saya memutuskan untuk membenamkan kaki saya di tanah berlumpur, daripada berjalan dengan aman melintasi sawah. TIDAK. Itu bukan aku.
Jadi saya terus bergaul dengan teman-teman saya yang atheis, agnostik, bahkan berbeda agama. Apakah ada yang salah?
Perkumpulan ini berlanjut hingga saya bekerja. Saya juga dekat dengan orang-orang yang masuk dalam kategori lesbian, homo, biseksualDan transgender (LGBT). Baca artikel saya di sini tentang LGBT.
Saya juga terus membaca buku-buku seperti karya Michel Foucault, Knowledge is Power, atau Sophie’s World, bacaan wajib bagi mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik.
Saya akhirnya memilih profesi jurnalis, bekerja 24 jam, kadang pulang pagi, yang menurut syariat Islam tidak ‘baik’ bagi perempuan. Tapi saya ya Saya tidak peduli karena saya merasa sedang melakukan sesuatu untuk masyarakat, menulis berita korupsi.
Mari kita putuskan
Namun, saya menerima banyak cemoohan dari mereka yang menganggap dirinya beriman. Menurut mereka, perempuan yang berhijab harus mematuhi syariat, baik perilaku maupun penampilannya.
Saya terkadang dikritik sebagai seorang liberal atau berasal dari generasi Siti Musdah Mulia, seorang dosen yang terkenal dengan kontroversi kesetaraan gendernya. “Mengenakan jilbab adalah hal yang liberal,” kata mereka.
Yang benar-benar perlu dipahami masyarakat adalah berhenti menuntut perempuan berhijab. Berhentilah mengatur bahwa wanita yang berhijab harus seperti Aisyah RA. Tampaknya mereka sudah melupakan sosok wanita karir seperti Khadijah.
Ketika seorang wanita memutuskan untuk berhijab, dia tidak berhenti pada sehelai kain yang menutupi kepalanya. Ada kalanya dia meragukan apa yang telah dia putuskan. Ada saatnya dia mencari kembali makna di balik hijabnya.
Ada kalanya ia merasa keimanannya lebih rendah dibandingkan wanita yang mengenakan rok pendek dan shalat tepat waktu. Ada kalanya ia lelah, karena Tuhan jauh darinya. Dia sama sepertimu, imannya naik turun.
Bahkan suatu hari nanti, mungkin saja, dia memutuskan dan memutuskan, dia akan melepasnya. Seperti temanku.
Saya menyerah pada teman saya yang memutuskan melepas hijabnya saat saya masih kuliah. Saya satu-satunya orang yang mendukungnya. Karena dipaksa berhijab sama saja dengan dipaksa tidak berhijab, seperti yang terjadi pada saya dulu.
Karena saya yakin, berhijab bukanlah hal yang mudah, di tengah masyarakat yang simbol adalah segalanya.
Tapi ada kalanya saya senang memakai hijab. Mungkin karena hal-hal kecil. Seperti saat saya menghadiri acara penghargaan Frederich Ebert Stiftung di Berlin pada tahun 2012.
Bertemu dengan Rahimullah Yusufzai – jurnalis asing pertama yang mewawancarai Osama Bin Laden – menyemangati saya hanya karena dia menyebut saya “Wanita berhijab hitam.”
Katanya, semua tamu mengenali saya karena hanya saya yang berhijab. Ia mengaku terkesan karena ada perempuan berjilbab yang menjalankan profesi jurnalis. Apalagi di Pakistan, kalau punya semangat belajar seperti Malala Yusufzai, bisa saja ditembak Taliban.
Belajar dari Yusufzai, terkadang sebuah kata yang tidak sebesar ayat bisa melekat di kepala kita hingga bertahun-tahun.
Bukankah semua orang menyukainya dan memberikan semangat kepada seluruh muslimah? Dengan tidak menuntut lebih. Mau berhijab atau tidak berhijab.
Karena seperti yang dikatakan ilmuwan Edward William Said, “Identitas tidak pernah mutlak.”
Bacalah kutipan inspiratif dari Said Orientalisme Di Sini.
Tidak ada hubungan antara seseorang yang berhijab dengan apa yang tersimpan jauh di dalam kepala, hati, atau bahkan sikapnya sehari-hari. Namun masyarakat lebih memilih untuk mendominasi kita dan kemudian secara sepihak memutuskan bagaimana kita harus bersikap, berkata dan bertindak. Saat mereka bertanya. —Rappler.com

Febriana Firdaus adalah jurnalis Rappler Indonesia. Ia fokus membahas isu korupsi, HAM, LGBT, dan pekerja migran. Febro, sapaan akrabnya, bisa disebutkan @FebroFirdaus.