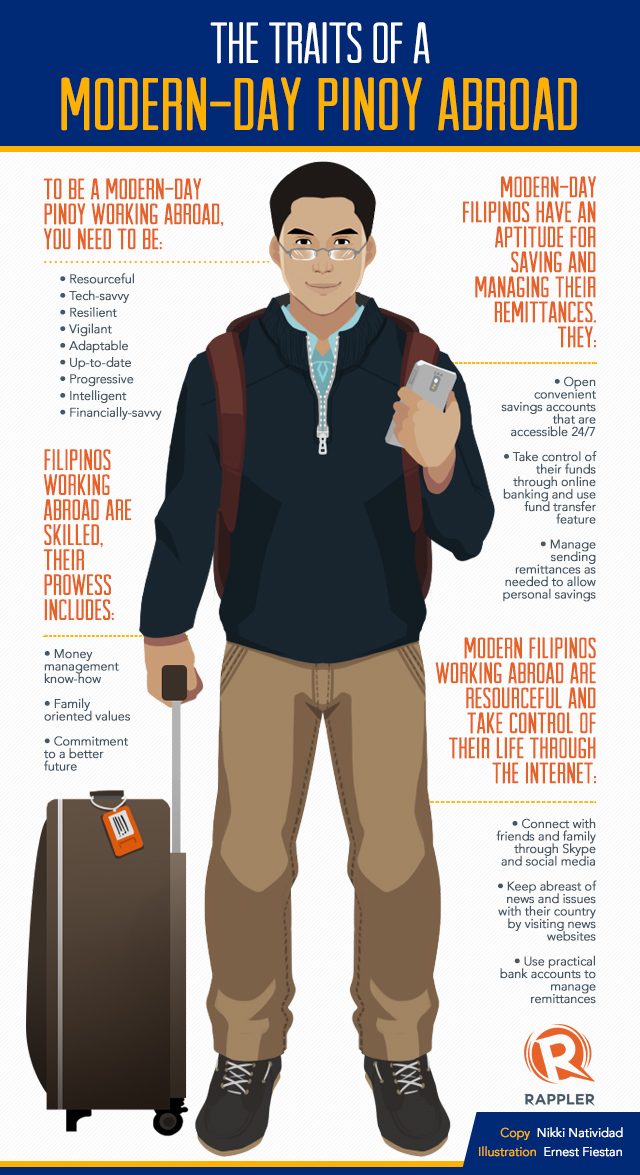Manusia perahu Rohingya: Jangan tutup mulut
keren989
- 0
Jika sejarah bisa bermanfaat, sejarah akan menunjukkan kepada kita bahwa pengungsi, baik dari Eropa Timur pada tahun 50an atau Indochina pada tahun 80an, akan berkembang dan sejahtera jika diberi kesempatan.
Lebih dari 2 minggu yang lalu, diaspora Vietnam yang berjumlah 3 juta orang memperingati 40 tahun jatuhnya Saigon, berakhirnya Perang Vietnam dan dimulainya eksodus mereka. Pada tahun-tahun berikutnya, lebih dari satu juta dari mereka melarikan diri dengan perahu ke negara-negara tetangga: Thailand, Malaysia dan Indonesia. Mirip dengan apa yang saat ini terjadi di laut Andaman dengan etnis Rohingya di Burma.
Mereka juga melarikan diri dari penganiayaan dan konflik etnis demi mencari kebebasan politik dan ekonomi. Untungnya bagi mereka, pihak Barat datang menyelamatkan mereka dengan merelokasi sebagian besar dari mereka, termasuk ayah saya. Sayangnya, bagi warga Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, tampaknya belum ada solusi yang dapat bertahan lama atau sebaliknya. Oleh karena itu, mereka tidak diinginkan berada di laut lepas untuk sementara waktu.
Krisis kemanusiaan terbaru yang terjadi di Asia Tenggara mengejutkan saya karena kedua sejarah tersebut terulang terlalu cepat. Meskipun terdapat tatanan dunia baru dengan kemakmuran dan konektivitas 4G yang belum pernah terjadi sebelumnya, meskipun ada semboyan ASEAN yaitu “Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas,” dalam hal meringankan penderitaan manusia dan menyelamatkan nyawa, kita sama sekali tidak mampu melakukannya.
Malaysia dan Indonesia sejauh ini telah merespons dengan menolak kedatangan “tidak sah” yang membawa ratusan warga Rohingya yang putus asa, sama seperti yang mereka lakukan terhadap warga Vietnam empat dekade sebelumnya. Singapura telah menyatakan bahwa mereka tidak menerima pengungsi dari negara mana pun. Sebaliknya, para pejabat Thailand dengan senang hati mengantar mereka pergi dengan menyediakan makanan dan air sebelum mereka pergi lebih jauh ke laut. Ke mana, sepertinya tidak ada yang peduli.
Sementara itu, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) yang bertugas merawat pengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia hanya bisa mendesak pemerintah regional untuk mengambil tindakan segera guna membantu mereka yang terdampar di laut.
Bagi banyak orang, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar, masalah ini harus diselesaikan dari sumbernya. Namun Burma bahkan tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negaranya dan malah menyebut mereka “Muslim Bengali yang tidak memiliki kewarganegaraan”. Faktanya, aturan resmi terbaru dari elit penguasa adalah bahwa hanya dengan menyebut kata “Rohingya” dalam pertemuan mendatang mengenai masalah ini akan menyebabkan mereka menarik diri dari partisipasi.
Diam bukanlah jawabannya
Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa permasalahan ini sangat kompleks dan memiliki banyak aspek, sehingga bahkan peraih Nobel terkenal Aung Sann Suu Kyi dari Burma, yang juga seorang pembela hak asasi manusia, tidak berani melakukan intervensi, karena takut hal tersebut akan memicu ketegangan dan pertumpahan darah lebih lanjut.
Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Huffington Post tahun lalu, dia dilaporkan berkata: “Saya tidak diam karena perhitungan politik. Saya tetap diam karena, tidak peduli di pihak mana saya berada, akan ada lebih banyak darah. Jika saya berbicara tentang hak asasi manusia, mereka (Rohingya) hanya akan menderita. Akan ada lebih banyak darah.”
Memang benar, mengingat kerusuhan yang terjadi antara Muslim Rohingya dan etnis Buddha Rakhine di negara bagian Rakhine di bagian barat Burma pada tahun 2012, situasi di sana masih suram dan tidak menentu. Tapi diam, saya kira, bukanlah jawabannya. Hal ini tentu saja tidak menghentikan terjadinya tragedi terbaru yang kini sudah terjadi di depan pintu ASEAN.
Jelas bahwa suara tunggal Aung Sann Suu Kyi tidak akan cukup. Tapi mengingat perawakannya, menelepon saja sudah menjadi awal yang baik. Dengan menyuarakan suaranya untuk menarik perhatian dunia terhadap penderitaan warga Rohingya, perempuan dan anak-anak yang sekarat karena kelaparan dan kehausan, para pemimpin regional dan negara-negara Barat akan merasa terdorong untuk bersatu dan segera mencari solusi. Mirip dengan apa yang mereka lakukan pada tahun 1979 di konferensi Jenewa yang menangani krisis pengungsi Indochina.
Pada saat itu, masalahnya sangat besar. Terdapat lebih dari 200.000 pengungsi Indochina yang mendekam di kamp-kamp di negara tetangga seperti Thailand dan Filipina. Dan ribuan lainnya tiba setiap hari dengan perahu dan jalur darat. Namun solusi jangka panjang ditemukan dalam waktu seminggu dan selama 10 tahun berikutnya, hampir 2 juta pengungsi Vietnam, Kamboja, dan Laos diproses dan diberikan suaka di negara-negara Barat.
Ini adalah tindakan yang patut dipuji, dipimpin oleh AS namun secara kolektif dilakukan oleh semua pihak, termasuk negara-negara yang tidak ada hubungannya dengan Asia Tenggara seperti Brazil dan bahkan Israel. Tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap etnis Rohingya, yang sering digambarkan sebagai salah satu kelompok minoritas yang paling teraniaya di dunia.
Jika sejarah bisa bermanfaat, sejarah akan menunjukkan kepada kita bahwa pengungsi, baik dari Eropa Timur pada tahun 50an atau Indochina pada tahun 80an, akan berkembang dan sejahtera jika diberi kesempatan. Dan mereka tidak hanya akan memberikan kontribusi besar kepada masyarakat di mana mereka berlindung, mereka juga akan segera membalas kebaikan yang sama kepada mereka yang mencari perlindungan seperti dulu.
Setelah topan super Haiyan yang meninggalkan jejak kehancuran besar di seluruh kepulauan Filipina 18 bulan lalu, komunitas Vietnam di luar negeri berhasil mengumpulkan lebih dari $2 juta untuk membantu upaya bantuan dan pembangunan kembali.
Sampai hari ini, sebuah plakat di sebuah sekolah yang dibangun kembali dan dibiayai oleh mantan manusia perahu asal Vietnam berbunyi: “Semoga kami melindungi Anda sebagaimana Anda melindungi kami pada saat kami membutuhkan.”
Andai saja warga Rohingya diberi kesempatan yang sama. – Rappler.com
Hoi Trinh adalah pengacara hak asasi manusia Australia asal Vietnam. Dia saat ini bekerja untuk VOICE, sebuah organisasi nirlaba yang membantu mengembangkan masyarakat sipil di Vietnam. Anda dapat menghubunginya di [email protected].
Artikel ini, yang pertama kali muncul di Interaksyon.com, diterbitkan ulang di Rappler dengan izin penulis.